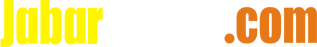Dilansir dari laman: National Geographic Indonesia.
Rel-rel di Stasiun Bekasi sudah menderit sejak subuh. Kereta Rel Listrik (KRL) pertama yang melaju mengarah ke Jakarta. Bagi warga Bekasi, Jakarta adalah lahan penghasilan hidup selain di kota ini sendiri. Awal perjalanan orang dan barang dari Bekasi menuju Jakarta menggunakan moda sepur ini telah dimulai sejak 1887 silam.
Masa itu, lintasan rel trayek Batavia-Bekasi selesai dibangun oleh Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij, perusahaan kereta api Belanda di Batavia. Tak ayal, lahirnya stasiun ini telah menambah kencang denyut Kota Bekasi yang sedang saya kunjungi ini.
“Bekasi,” tulis Pramoedya Ananta Toer, “adalah kota yang berbekas di hati. Kota yang membekasi”. Kalimat lirik itu ia ketik pada babak pembuka novel Di Tepi Kali Bekasi. Namun, saya membutuhkan kesabaran lebih untuk bisa bertahan di Bekasi ini. Di pusat kotanya, bermacam kendaraan tumpang tindih, saling merangsek di simpang-simpang jalan beraspal.
Didi Kaspi Kasim merasa demikian pula. “Bekasi ini pelik banget,” kata Didi kepada saya. Laju kotanya, di mana industri dan masyarakat bertemu masih campur aduk. “Kadang, pembangunan juga memberikan kesulitan kepada manusia di sekelilingnya,” lanjut pria yang saya temui di Kota Bekasi ini. Bekasi memiliki tantangannya sendiri; keseimbangan pembangunan kota dengan kenyamanan manusia yang menghuninya.
Jauh sebelum tumbuh menjadi kawasan padat dan penuh industri seperti hari ini, Kota Bekasi memang telah dikenal ramai sejak lama. “Bekasi, distrik dari afdeling Meester Cornelis, salah satu daerah yang ramai oleh pedagang dari hilir hingga ke dalam,” catat Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië pada 1896 silam. Bekasi, rupanya memang ditakdirkan menjadi kota yang riuh. Namun, Bekasi dulu tak seperti sekarang.
Pada masa kolonial Belanda, lebih dari separuh tanah-tanah di Bekasi tidak dikuasai oleh penduduk lokal. “Hampir seluruh tanah di Bekasi dari Sungai Cakung hingga Sungai Citarum dikuasai oleh orang-orang Tiongkok,” catat surat kabar Java Bode, salah satu koran tertua di Batavia, pada 19 Oktober 1853. Sebab itu, kata sejarawan Akhir Matua Harahap, orang-orang Belanda menyematkan embel-embel Provinsi Cina pada Bekasi.
Kendaraan yang saya tumpangi sedang mengarah ke Tambun, wilayah di bagian timur Kota Bekasi. Di depan saya, Didi dengan kendaraan roda duanya merangsek di sela-sela kepadatan jalan kota. Ia sedang melanjutkan perjalanannya menyusur pesisir utara Pulau Jawa.
Di perjalanan, mobil yang saya naiki melintas di Taman Kota Bekasi. Taman ini sama seperti taman-taman lain di kota-kota padat di Indonesia; kumpulan pohon yang dilingkung pengap polusi industri dan kendara bermesin. Sebelum menjadi tempat rekreasi orang-orang urban masa sekarang, taman ini dulunya adalah pusat pemerintahan kolonial Belanda. Dan di taman ini pula beberapa orang-orang Tambun menemui nasib nahas berabad lampau.
Pagi diawal April tahun 1869, tiga ratusan orang sedang menuju Tambun dari Cimuning. Rombongan ini dipimpin oleh Rama, seorang jawara asal Cirebon. Tujuan mereka adalah merebut tanah-tanah partikelir yang dikuasai oleh para tuan tanah yang tamak.
Mendengar kabar ratusan orang sedang bergerak ke Tambun, polisi- polisi Belanda bersiaga. Kemudian, pertempuran pun pecah.
“Pada malam hari, dari tanggal 2 dan 3, kerusuhan terjadi di Tambun. Asisten Residen Meester Cornelis dan beberapa personil polisi tewas terbunuh. […]sebagian dari pemberontak itu berhasil ditawan dan dipindahkan ke Bekasi,” begitu tertulis dalam harian Bataviaasch Handelsblad empat hari usai peristiwa itu terjadi.
Sekitar 302 orang berhasil tertangkap. Menyusul dua bulan kemudian Rama turut dibui. Namun, ia mati sebelum diadili. Bagi penduduk Tambun, Rama dan pengikutnya adalah pejuang. Tapi, di mata kolonial mereka adalah pemberontak. Dua orang dari pengikut Rama dihukum gantung bersama enam terpidana lain setahun kemudian. Kolonial Belanda, entah mengapa, mencap orang-orang itu sebagai acht Tamboenmoordenaars –delapan jagal dari Tambun. Delapan orang malang itu digantung di Alun-Alun Bekasi, taman yang tadi saya lewati.
“Bangunan ini dulu milik seorang Raja Beras,” kata Slamet, 62 tahun, kepada saya di beranda sebuah rumah berhalaman luas di Tambun. Rumah ini dibangun pada 1906. Pemiliknya adalah Khouw Tjeng Kee, seorang tuan tanah partikelir. Ialah yang disebut oleh Slamet itu sebagai seorang Raja Beras. Tambun, dulunya memang jaya sebagai daerah penghasil beras. “Orang-orang sini menyebut rumah ini Gedung Gede,” terang Slamet.
Khouw Tjeng Kee tak lama berada di bangunan ini. Ketika tentara-tentara Jepang masuk ke Indonesia, bangunan ini diambil untuk dikuasai. Mereka menjadikan rumah ini sebagai salah satu basis militer. Usai kemerdekaan, bangunan ini diambil alih oleh pasukan republik dan dijadikan sebagai pusat komando perjuangan Republik Indonesia di Bekasi. Dari sejarahnya itulah bangunan bergaya Eropa ini dinamakan Gedung Juang Tambun hingga hari ini.
Bekasi, kota yang kata Didi pelik ini, telah tercatat dalam kitab sejarah sebagai kota yang pernah membuat bangsa-bangsa penjajah gentar. Kisah kepahlawanan warga Kota Bekasi setara dengan kepahlawanan rakyat Surabaya pada masa kemerdekaan Indonesia. Sebab itu, kota ini juga membekas dalam diri Chairil Anwar.
Penyair flamboyan yang mati muda itu menaruh Bekasi dalam satu puisinya yang melegenda. Kenang/kenanglah kami/yang tinggal tulang-tulang diliputi debu/Beribu kami terbaring antara Karawang-Bekasi.
Kisah ini merupakan bagian dari jurnal perjalanan National Geographic Indonesia dalam menjelajahi kota-kota pesisir. (Red)