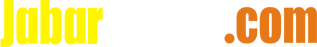Penulis: Syafbrani (Pengurus Bidang Pendidikan DPD PUI Kota Bogor dan bergiat di Universitas Trilogi)
Mengapa kita mempersoalkan gelar (kehormatan) akademik yang diraih oleh orang lain? Untuk kemudian kita pun terjebak dalam ruang debat tanpa muara. Terjerembab dalam ruang penilaian yang tak terdefinisikan. Parahnya lagi ketika landasannya hanya persoalan suka dan benci. Dialektika pro – kontra pun akan semakin mencuat. Bisa-bisa tak terhentikan. Bahkan kelak, sampai kiamat?
Padahal, seharusnya, ketika penetapan pemberian gelar (apa pun bentuk dan jenis gelarnya) sudah melalui rangkaian dan proses yang seharusnya dilewati. Artinya, final sudah dan itu sah. Persoalan suka atau tidak, tidak bisa dijadikan syarat untuk mendiskualifikasikannya.
Baca Juga: Empat Kecamatan di Cianju Dapat Program Rutilahu, Anggaran Rp1,9 Milyar Sasar 95 Penerima
Bahkan, ketika ruang debatnya beralih pada kapasitas yang dimiliki. Kompetensi. Pun kita tetap tidak bisa melegalisasikan penilaian pribadi. Alat ukur penilaian kita apa? Pandangan politik? Gosip-gosip tetangga? Atau, suka dan tidak lagi? Sekali lagi, ketika semuanya sudah melewati rangkaian dan proses sesuai aturan. Itu sah.
Baca Juga: Jangan Sampai Dilakukan! Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Merusak Sendi, Salah satunya Kretek
Baca Juga: Ini Alasanya Kenapa Kerja Lembur Itu Berbahaya Menurut Dr. Saddam Ismail
Dalam panggung demokrasi, yang juga menjunjung tinggi hukum, ada alat ukur sehingga sesuatu itu diterima atau ditolak: keabsahan. Bahkan andai ingin mengubah keabsahan tersebut, haruslah dilakukan dengan cara yang sah dan didukung oleh aturan yang sah pula. Bukankah begitu?
Persis, ketika kita pertama kali menyandang predikat lulusan sekolah dulu. Harus melalui berbagai prosedur yang sah. Mulai dari mengikuti prosedur saat mendaftarkan diri ke sekolah, membawa syarat-syarat yang sah, sampai akhirnya lulus mendapatkan ijazah. Sah!
Ijazah yang sah ini kemudian digunakan untuk melanjutkan studi ke tahap selanjutnya, misalnya ke perguruan tinggi. Perguruan Tinggi yang juga harus sah.
Sama seperti di sekolah. Ketika semua prosedur dilalui, barulah kemudian bisa lulus dan mendapatkan ijazah. Sah!
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Siloam Hospital Purwakarta Nol, Pelayanan Sudah Kembali Normal
Baca Juga: Jadi Saksi Kasus Kekerasan Pelajar di Kota Bogor, Tiga Siswa SMA YPHB di DO
Pertanyaannya kemudian, misalnya ketika lulus kuliah pertama kali, apakah ada yang peduli tentang kelayakan kita mendapatkan gelar tersebut? Apakah ada yang mempertanyakan kompetensi yang kita miliki terkait dengan gelar kesarjanaan itu?
Baca Juga: Tiga Efek Stres Pada Tubuh Menurut Dr. Kevin Mak, Salah Satunya Sulit Tidur
Baca Juga: Banjir Rendam Ribuan Rumah dan Ratusan Hektar Pertanian di Serdang Bedagai, Warga Belum Mengungsi
Adanya, ketika gelar itu diraih, kita malah tenggelam dalam panggung selebrasi akademik bersama toga kebesaran yang digunakan. Terbius dengan gelar yang tertulis indah di ijazah. Tidak ada waktu lagi untuk sedikitpun mempertanyakan dua hal tadi: keabsahan dan kompetensi. Walaupun saban tahun kita selalu disuguhi fenomena tentang salah jurusan, kompetensi lulusan, daya saing lulusan, dan sebagainya.
Bisa jadi karena fenomena itu sudah dipandang biasa. Akhirnya kita terbiasa.
Bisa jadi juga, perlahan tapi pasti, kita bersama sudah mulai menyepakati bahwa kompetensi tidak semata-mata harus linear dengan gelar akademik. Atau sebaliknya, gelar akademik tidak semata-mata menunjukkan kompetensi yang sesuai dengan gelarnya. Ada sudut pandang lain. Sudut pandang yang kita tidak sempat melihatnya. Termasuk untuk melihat ke diri sendiri.
Bukti sederhananya, bukankah kita sering melihat fenomena yang secara kasat mata sangat kontradiktif: kompetensinya dipandang nihil, tapi karirnya cepat melesat. Atau sebaliknya: berkompetensi tinggi, tapi selalu kandas menapak jabatan. Kandas hanya karena variabel yang di luar perkiraan. Lagi, jika memandangnya dengan sudut pandang normal tentunya.
Baca Juga: Makan Pedas Bisa Bikin Perut Sakit Hingga Diare? Ini Penjelasannya
Bisa jadi, awal mendengar atau mengalami kisah – kisah seperti ini, akan ada rasa ingin mempersoalkannya. Tidak hanya menjadi perbincangan atau gunjingan. Bahkan bisa jadi timbul hasrat untuk ‘menggugat’.
Baca Juga: Walah! Ibu Rumah Tangga di Garut Jual Ratusan Botol Miras, Pembelinya Ada Anak di Bawah Umur
Baca Juga: Makan Pedas Bisa Bikin Perut Sakit Hingga Diare? Ini Penjelasannya
Namun, pastinya lama-kelamaan akan kembali seperti biasa. Perlahan, waktulah yang akhirnya seperti memaksa kita untuk aklamasi memandangnya dengan biasa-biasa saja. Akhirnya kita pun terbiasa. Setidaknya lupa.
Maka, bisa jadi, kelak lambat laun pro – kontra terhadap pemberian gelar (kehormatan) akademik akan mencapai puncaknya: biasa saja. Semua berpeluang mendapatkannya.
Persis saat para wisudawan strata satu meraih gelar sarjananya. Juga persis seperti anak – anak sekolah yang sudah mulai terbiasa diwisuda dengan menggunakan pakaian toga itu. Tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait keabsahan, kelayakan dan kompetensi. Biasa saja.
Terakhir, karena dalam panggung demokrasi, yang juga menjunjung tinggi hukum, ada satu hal yang membuat sesuatu itu dipandang sah dan layak: kesepakatan bersama. Apalagi kesepakatan bersama ini disuarakan oleh para pihak yang berkuasa membubuhkan cap sah. Sah! ***
*Tulisan ini sepenuhnya tanggung jawab penulis