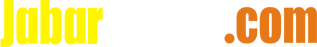JABARNEWS | BANDUNG – BMKG menegaskan kalau cuaca gerah yang belakangan kerap dirasakan tidak berkaitan dengan fenomena peningkatan kelembaban global.
Kepala Subbidang Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Siswanto menegaskan kalau cuaca gerah yang belakangan dirasakan di Indonesia memang berbeda dari gelombang panas.
“Oh ini hal berbeda, walaupun indikatornya bisa sama,” tuturnya dilansir dari laman Cnnindonesia, Rabu (13/5/2020).
Menurut Siswanto, panas gerah yang terjadi belakangan masih terkait dengan peristiwa pertengahan April lalu akibat peralihan ke musim kemarau.
Peralihan ke musim kemarau ini mengakibatkan suhu udara yang tinggi, kelembaban udara yang rendah. Hal ini terjadi karena kondisi langit cerah dan kurangnya awan. Sebab, pancaran sinar matahari langsung lebih banyak diteruskan ke permukaan Bumi.
Hal senada diungkap Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Dodo Gunawan. Sebab, menurutnya peningkatan kelembaban global itu kebanyakan terjadi di kawasan lintang tinggi yang mengalami empat musim, dimana saat musim panas, suhu biasanya bahkan melebihi daerah tropis.
“Ini yang sejauh ini dikenal sebagai heat wave,” ujar Dodo.
Hal ini diungkap BMKG menanggapi studi dari Observatorium Bumi Lamont-Doherty Universitas Colombia. Studi itu menyebut serangan panas dan kelembaban ekstrim telah terjadi sejumlah wilayah di dunia.
Dalam studi yang dimuat dalam jurnal Science Advances itu mengidentifikasi ribuan serangan panas dan kelembaban ekstrim yang sebelumnya jarang atau belum pernah terjadi di Asia, Afrika, Australia, Amerika Selatan dan Amerika Utara, termasuk di wilayah Pantai Teluk AS.
Terkait dengan gelombang panas, Dodo menyampaikan pihaknya belum menemukan kasus heat wave di Indonesia. Dia menduga hal itu karena fluktuasi suhu di Indonesia atau wilayah tropis tidak terlalu tinggi.
“Pada saat-saat setiap lokasi mencapai posisi terdekat dengan matahari, memang biasanya suhu terasa panas,” ujarnya.
Berdasarkan studi tersebut, peningkatan panas dan kelembaban ini lebih cepat dari prediksi semula. Penelitian sebelumnya memproyeksikan fenomena tersebut terjadi pada akhir abad ini.
Peningkatan kelembaban global disebut berbahaya bagi manusia. Sebab, kelembaban udara yang tinggi membuat manusia sulit berkeringat ketika mereka kepanasan. Padahal keringat adalah cara alami tubuh untuk melepas panas. Sehingga, hal ini bisa menyebabkan manusia tewas akibat tak bisa melepas panas.
Colin Raymond yang memimpin studi ini menyebut panas dan kelembaban ekstrem dapat membuat evaporasi keringat melambat. Dalam kasus yang paling ekstrim, itu bisa berhenti. Bahkan, orang yang kuat dan sehat secara fisik yang beristirahat di tempat teduh tanpa pakaian dan akses ke air minum akan mati dalam beberapa jam.
Di sepanjang Teluk Persia misalnya, para peneliti mencatat selusin fenomena panas dan kelembaban ekstrim. Meski terbatas pada daerah tertentu dan hanya berlangsung beberapa jam, tapi frekuensi dan intensitas fenomena itu terus mengalami peningkatan.
“Studi sebelumnya memproyeksikan bahwa ini akan terjadi beberapa dekade dari sekarang, tetapi ini menunjukkan itu terjadi sekarang,” kata Raymond, melansir Science Daily.
Menganalisis data dari stasiun cuaca sejak 1979 hingga 2017, penulis menemukan bahwa kombinasi panas dan kelembaban yang ekstrim meningkat dua kali lipat selama periode penelitian. Insiden yang berulang muncul di sebagian besar India, Bangladesh dan Pakistan; Australia barat laut; dan di sepanjang pantai Laut Merah dan Teluk California di California.
Data tertinggi yang berpotensi fatal terlihat 14 kali di kota-kota Dhahran/Damman, Arab Saudi; Doha, Qatar; dan Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab. Lalu terjadi juga di sebagian Asia Tenggara, Cina selatan, Afrika, dan Karibia. (Red)